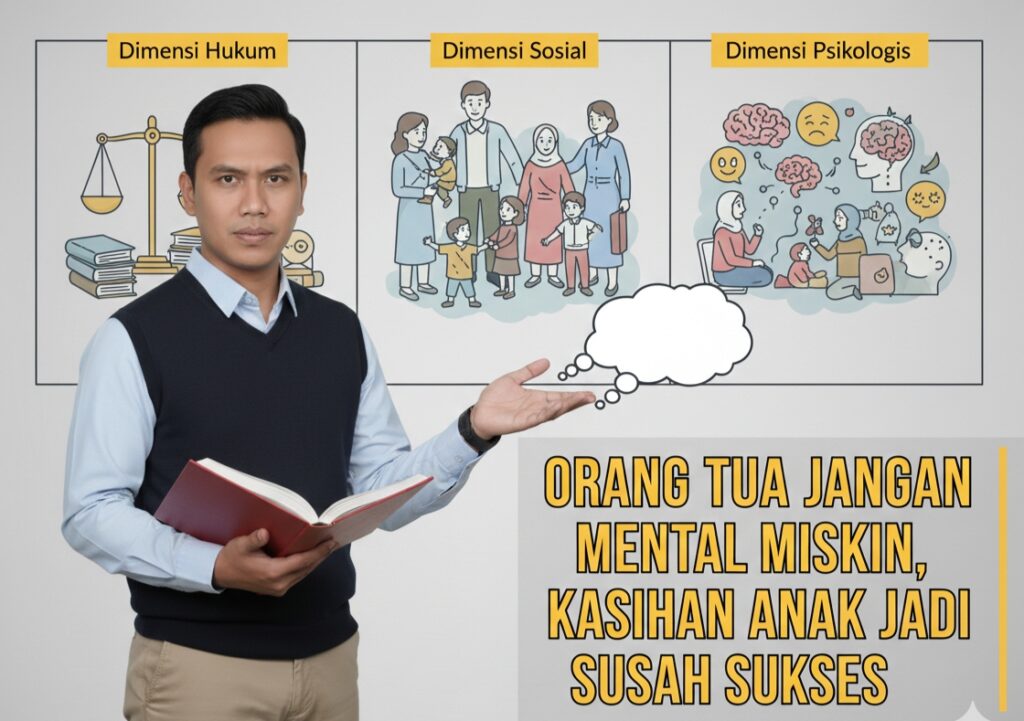![]()

Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P (Advokat dan Pengamat Militer)
Dalam tataran normatif hukum dan dinamika operasional penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menerapkan diklat semi-militer bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026—dengan narasi “masuk barak”—memerlukan analisis multidimensi yang melampaui tataran retorika administratif semata. Sebagai advokat yang memegang prinsip kepastian hukum dan pengamat militer yang memperhatikan integritas sistem pembinaan tenaga pelayanan publik, saya melihat langkah ini bukan hanya sebagai upaya peningkatan disiplin, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan norma profesionalisme yang sedang teruji oleh kompleksitas tantangan di lapangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PPIH memiliki fungsi utama sebagai pembina, pelayan, dan pelindung jamaah, dengan kewajiban untuk memastikan kelancaran ibadah sesuai dengan prinsip agama dan regulasi negara. Konsep “barak” dalam konteks ini—yang merujuk pada sistem pembinaan intensif ala militer—didirikan atas dasar logika operasional: kondisi di Makkah dan Madinah, dengan medan yang ekstrem dan jumlah jamaah yang masif, membutuhkan tenaga yang tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga tangguh secara fisik dan mental. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pelatihan selama 3–4 minggu di barak akan mencakup tiga pilar utama: kesiapan fisik, fikih dasar haji, dan bahasa arab dasar—elemen yang dianggap krusial untuk mengatasi keluhan tentang kinerja petugas yang belum optimal tahun-tahun sebelumnya. Dari perspektif militer, hal ini sejalan dengan prinsip training as combat, di mana pelatihan dirancang untuk mensimulasikan tantangan aktual di lapangan.
Secara normatif hukum, kebijakan ini memiliki dasar yang kokoh dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur tentang standar kompetensi dan pembinaan petugas. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban negara dalam memfasilitasi ibadah juga menjadi landasan filosofis, di mana negara berkewajiban untuk menyediakan tenaga yang mampu melindungi jamaah dari risiko fisik dan non-fisik. Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan tenaga kesehatan dalam diklat ini memperkuat dimensi intersektoral, sesuai dengan prinsip integrated defense system yang diterapkan dalam operasi publik berisiko tinggi. Letkol ARM Tulus Widodo, anggota Tim Pokja Diklat PPIH 2026, menekankan bahwa pembinaan jasmani (binjas)—meliputi jalan sehat, senam kebugaran, dan latihan baris-berbaris—dirancang untuk membentuk karakter dan kedisiplinan, bukan untuk menjadikan petugas sebagai prajurit. Ini adalah nuansa penting: pendekatan semi-militer berfungsi sebagai tool of empowerment, bukan instrumen militarisasi pelayanan agama.
Dari perspektif pengamat militer, saya melihat implikasi lebih luas dari kebijakan ini terhadap kultur adaptasi dan ketahanan operasional. Haji bukan hanya ibadah individu, tetapi juga operasi logistik skala besar yang membutuhkan koordinasi presisi, kemampuan mengambil keputusan cepat, dan daya tahan fisik yang tinggi. Pelatihan semi-militer akan menanamkan nilai-nilai seperti esprit de corps, tanggung jawab kolektif, dan rasa bangga dalam melayani jemaah—nilai-nilai yang menjadi inti dalam organisasi militer. Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistio Rek Soprod Jo menegaskan bahwa disiplin yang dibentuk melalui diklat ini adalah “disiplin untuk melayani”, yang menegaskan bahwa esensi pelayanan agama tidak tergerus oleh struktur pelatihan yang ketat. Hal ini sejalan dengan prinsip mission command dalam militer, di mana setiap anggota diberi wewenang untuk bertindak sesuai dengan tujuan utama—yaitu kesejahteraan jamaah.
Namun, perlu diperhatikan risiko potensial: eksesibilitas dalam penerapan pendekatan semi-militer yang dapat mengurangi nuansa humanis dalam pelayanan. Sebagai advokat, saya menyarankan agar Kemenhaj menetapkan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa pelatihan tidak menimbulkan tekanan psikologis berlebihan atau melanggar hak-hak petugas. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas diklat harus dilakukan dengan mengukur indikator seperti tingkat kepuasan jamaah, jumlah insiden yang teratasi, dan kesiapan petugas dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, prinsip proportionalitas dalam hukum publik menjadi kunci: ketegasan dalam pelatihan harus seimbang dengan kepekaan terhadap karakteristik ibadah haji sebagai aktivitas spiritual.
Kesimpulannya, kebijakan “masuk barak” untuk calon petugas haji 2026 adalah langkah inovatif yang memadukan prinsip militer dengan esensi pelayanan agama. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung upaya ini dengan memastikan bahwa pelatihan tetap berfokus pada tujuan utama: memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji. Sebagai pengamat militer, saya melihat ini sebagai contoh bagaimana prinsip-prinsip operasional militer dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan humanis. Institusi pendidikan dan organisasi keagamaan juga harus berperan dalam membangun sinergi, sehingga diklat semi-militer tidak hanya menghasilkan petugas yang disiplin, tetapi juga memiliki empati dan pemahaman mendalam tentang esensi ibadah haji.